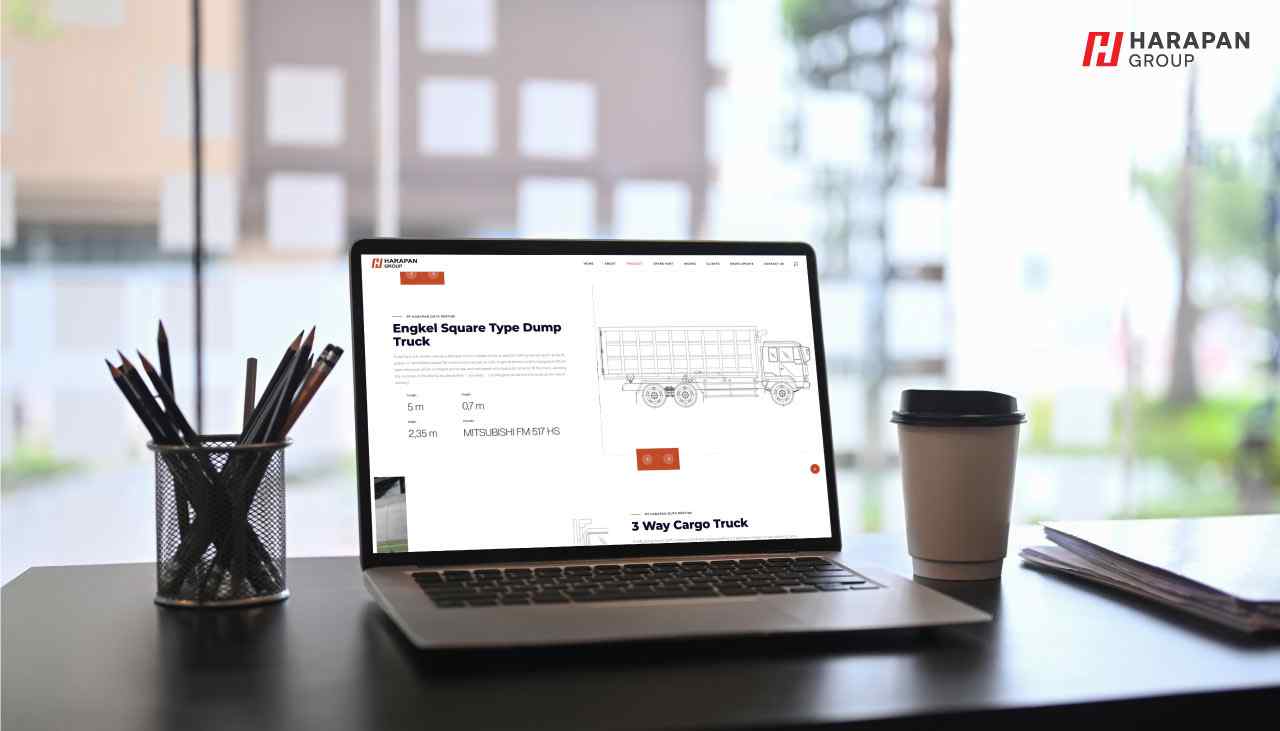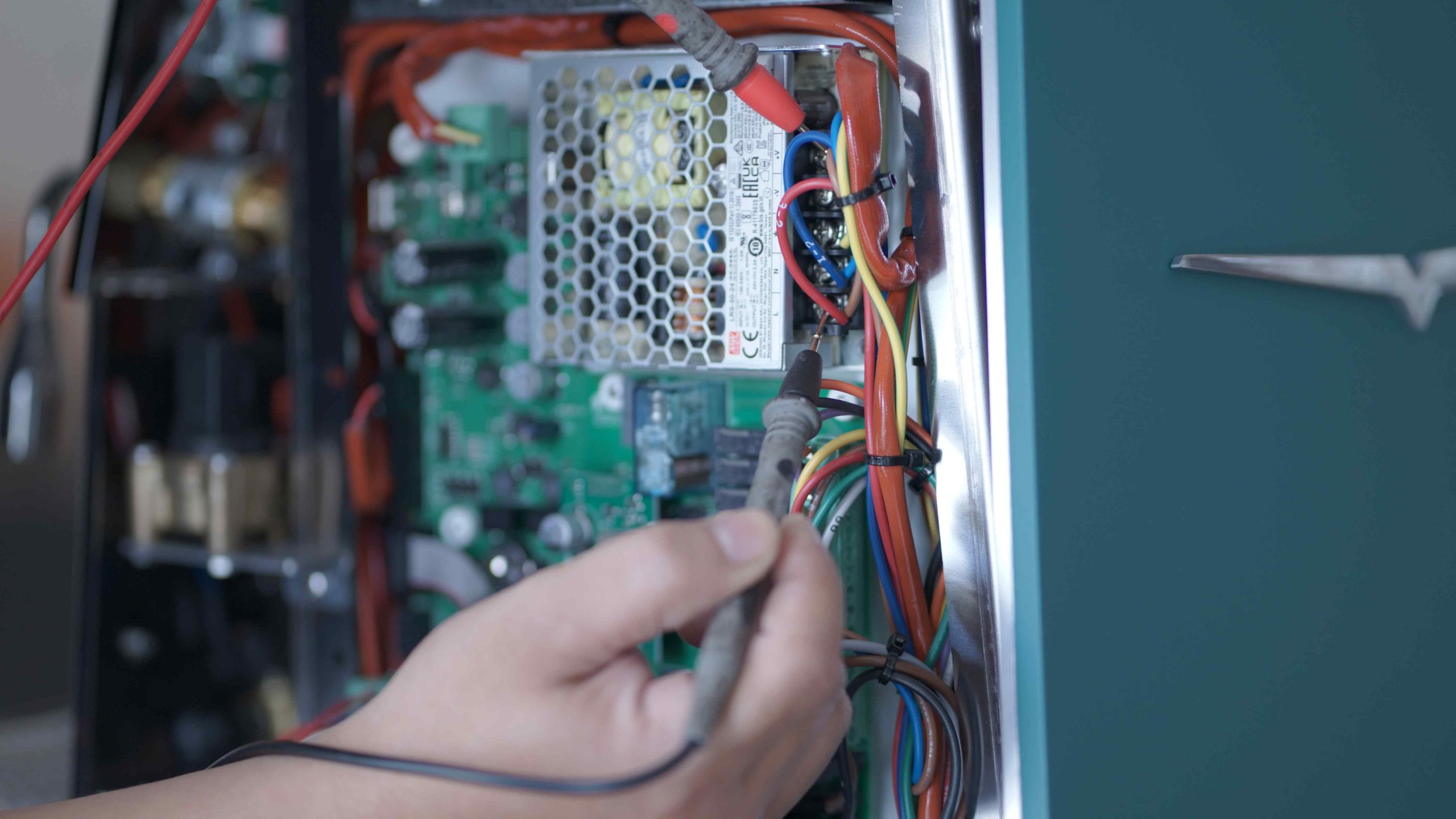Apabila novel ini dikatakan sebagai sebuah novel tentang pendakian atau tentang kehidupan di gunung, barangkali kita telah tertipu. Fokus utama karya Eko Darmoko ini justru mengacu pada relasi Ranu dengan perempuan.
—
KIRANYA benar bahwa dalam menulis buku harian atau memoar selalu melibatkan nostalgia. Secara umum, nostalgia dipahami sebagai kerinduan akan orang, ruang, atau peristiwa yang terjadi di waktu silam. Namun, berbicara tentang nostalgia pada dasarnya berbicara tentang bayang-bayang emas masa lalu dan relasinya dengan kondisi masa kini dan akan datang.
Dengan kalimat lain, manusia yang terasing dari lingkungannya kini. Setidaknya, begitulah yang saya tangkap saat membaca novel Anak Gunung.
Nostalgia erat kaitannya dengan cara ingatan bekerja. Merleu-Ponty menyatakan bahwa mengingat bukanlah memfokuskan pikiran untuk membentuk imaji tentang masa lalu. Melainkan menembus dalam-dalam horizon masa lalu untuk meleraikan perspektif satu demi satu guna menghadirkan keutuhan pengalaman.
Kant menyatakan salah satu fungsi ingatan adalah mereproduksi representasi. Dalam proses reproduksi, representasi yang dihadirkan cenderung bergeser dan bercampur dengan situasi terkini pengingat. Brian Turner menyatakan bahwa nostalgia berkaitan dengan proses katarsis individu dan berkaitan dengan komitmen moral seseorang. Agaknya, itulah yang menggerakkan roda kisah dalam Anak Gunung.
Novel ini dibuka dengan perjumpaan Ranu –seorang penulis– dengan kawan lamanya, seorang perempuan peranakan Jepang-Indonesia, Ohori, di Kitakyushu, Jepang. Perjumpaan yang memberikan rangsang pada Ranu untuk mengunjungi kembali buku harian yang telah bertahun-tahun tidak dijamah.
Rangsang yang membuatnya ’’harus menerawang jauh, menggeledah kenangan, mengingat lagi keping-keping peristiwa yang terjadi di masa lampau, kemudian merakitnya kembali menjadi bangunan yang utuh” (hlm 8). Kisah lalu bergulir kembali dengan ingatan Ranu pada saat ia kuliah di Surabaya.
Sebagai sebuah strategi naratif, pernyataan Ranu menunjukkan bahwa novel ini merupakan sebuah buku harian. Namun, bagi pembaca yang kurang teliti, bentuk novel sebagai buku harian tidak akan tertangkap.
Sebab, penulisan peristiwa di dalam novel merupakan konvensi penuturan prosa pada umumnya, yakni dengan narasi dan dialog antartokoh. Tidak akan kita temui titimangsa persisnya terjadi peristiwa. Meskipun demikian, bentuk novel sebagai buku harian merupakan sebuah hal penting dalam memahami keseluruhan novel.
Novel ini sampai di tangan pembaca setelah Ranu merakitnya kembali. Dalam perspektif naratologi, hal tersebut mengisyaratkan bahwa segala informasi yang sampai pada pembaca merupakan suatu hal yang telah mendapatkan persetujuan dari narator.
Ini berarti informasi yang didapat bukan dalam bentuk lampau, melainkan masih relevan dengan kondisi kini. Pernyataan Ranu bahwa ia akan menyanggupi permintaan tokoh Fatimah untuk menikah meskipun ia adalah lelaki sisa (halaman 58), misalnya, tidak lagi merupakan pernyataan yang berasal dari masa lalu, tapi sebuah pernyataan yang relevan dengan situasi tokoh terkini.
Buku harian bersifat personal dan berfungsi seperti halnya album kenangan, yakni sebagai monumen yang dapat dijinjing tentang segala yang telah lalu dan ingin dikenang. Kita tahu, dalam menulis buku harian tidak semua hal masuk di dalamnya.
Selain seleksi peristiwa, dalam buku harian terdapat pula sebuah pola emosi yang terbentuk melalui reaksi terhadap sebuah peristiwa. Begitu pula halnya dengan Anak Gunung. Dalam upaya Ranu mencipta bangunan utuh, dapat kita lihat terdapat repetisi yang tidak berkaitan dengan judul novel.
Judul Anak Gunung membingkai pembaca untuk mengarah pada kisah tentang pendakian atau tentang kehidupan di gunung. Memang pendakian erat kaitannya dengan kehidupan tokoh dalam novel, baik sebagai hobi, pekerjaan, maupun latar belakang tokoh.
Anak gunung dalam novel mengacu pada dua hal utama, yakni asal usul tokoh utama novel bernama Ranu yang berasal dari kaki Gunung Semeru dan hobi mendakinya. Dua acuan berkaitan dengan judul itu hadir sebagai peletak dasar kedirian tokoh. Namun, apabila novel ini dikatakan sebagai sebuah novel tentang pendakian atau tentang kehidupan di gunung, barangkali kita telah tertipu.
Fokus utama novel tampaknya mengacu pada relasi Ranu dengan perempuan. Terdapat enam tokoh perempuan dalam novel yang dapat kita kategorikan dalam dua kutub. Fatimah, Desi, dan Rika berada dalam kutub berlawanan dengan Stephanie, Grace, dan Ohori.
Pembagian kutub itu didasarkan pada ketertarikan perempuan terhadap ranah sastra. Juga, kutub penyuka sastra merupakan para perempuan yang berakhir di ranjang dengan Ranu. Kutub itu dapat dibagi pula berdasar tubuh perempuan.
Perempuan penyuka sastra merupakan perempuan dengan kecantikan non-Indonesia. Stephanie berparas Latin (halaman 102), Grace peranakan Amerika-German (halaman 30), dan Ohori peranakan Indonesia-Jepang (halaman 78).
Jika kita cermati lebih dalam, dikotomi itu bersifat hierarkis berkaitan dengan tingkat kecerdasan seorang perempuan. Timbul pula kelakar terkait penokohan Ranu sebagai penulis, apakah menyukai sastra merupakan syarat untuk dapat bersetubuh dengan penulis? Ada pula wacana lain tentang liyan sebagai sebuah hal yang eksotis yang dapat diarahkan pada relasi maskulin-feminin atau pada wacana liyan baik itu dalam perspektif psikoanalisis atau kolonial.
Menarik untuk dicermati, dikotomi perempuan dalam novel merupakan cermin dari dikotomi lainnya: Ranu merupakan seorang mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Airlangga yang justru lebih banyak membaca karya asing, dapat kita dapati nama-nama sastrawan Eropa dan penjelasan singkat tentang karyanya berserakan di dalam novel; menulis kreatif (sastra)-menulis tidak kreatif (akademis); desa (Lumajang)-kota (Surabaya).
Dikotomi itu kemudian menimbulkan pertanyaan vital teks ini, pada posisi mana Ranu berada pada dikotomi-dikotomi dalam teks? Saya kira novel ini berupaya menghadirkan jawaban atas pertanyaan itu. Anak Gunung dapat dinyatakan merupakan sebuah metafor atas liminalitas. Layaknya pendaki yang merasa gunung adalah rumah sebelum akhirnya harus pulang. (*)
—
- JUDUL BUKU: Anak Gunung
- PENULIS: Eko Darmoko
- CETAKAN: I, Juli 2022
- PENERBIT: Pelangi Sastra
- HALAMAN: vii + 254 halaman
- ISBN: 978-623-6937-53-2
Credit: Source link